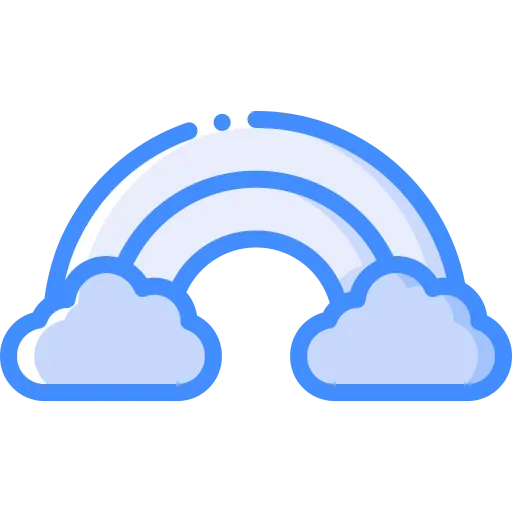
Sahabat Awan (Bagian 4)
Pahitnya Hukuman
Hukuman adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh orang di seluruh dunia. Tapi dari sebuah hukuman itu bisa terbentuk disiplin hidup. Namun ada juga orang yang menyalahgunakan hukuman menjadi sebuah ketidakteraturan. Kelas 5 adalah kelas yang menyeramkan bagiku dan teman-teman.
Kenapa tidak, karena di kelas 5 kami memiliki wali kelas bernama ibu Ita yang super sangar di dunia ini. Baginya hukuman adalah peta kehidupan kemana orang itu akan melanjutkan hidupnya di kemudian hari. Inilah uraian beberapa kali hukuman menghampiriku.
Hukuman Pertama
Pagi itu aku dan teman-teman baru sampai di kota Sampit. Seperti biasa kami akan melanjutkan perjalanan kaki ke sekolah melewati deretan toko yang cukup panjang. Di antara deretan toko itu, toko emas adalah toko yang paling mendominasi. Waktu itu kira-kira pukul 5.45 WIB, banyak toko yang belum membuka pintu rezekinya. Kami berjalan berjejer seperti bangunan tembok yang kokoh. Kami berjalan semaunya melihat keadaan yang sunyi sengang. Beberapa toko terlihat mulai membuka bilik cahayanya.
Tepat di hadapan kami sebentar lagi berhadapan dengan bundaran simpang empat. Itu artinya sebentar lagi kami akan sampai ke sekolah. Belum sempat deretan toko itu kami selesaikan. Pahing berteriak melihat uang yang berhamburan di depan salah satu toko emas. Kami hanyalah anak kecil yang berjiwa malu-malu kucing. Kami terpaku menghadapi uang yang terdiri dari beberapa uang lembaran Seribu Rupiah, beberapa uang lembaran Sepuluh Ribu Rupiah dan beberapa uang lembaran Dua Puluh Ribu Rupiah. Kami mencoba mengira-ngira apa yang terjadi pada toko ini malam tadi sehingga meninggalkan uang yang segini banyaknya.
“Eg, mau diapakan uang ini?” tanya Dimas.
“Sebentar lagi jam masuk kelas. Kita ambil saja uang ini dulu, nanti pulang sekolah kita mampir lagi ke toko ini dan kembalikan uang ini. Daripada kita tinggalkan, nanti diambil orang jahat” kata Egi dengan yakin.
Kami pun menyetujui saran Egi. Uang yang berjumlah 133 ribu itu kami simpan di dalam kotak pensil Siti. Kemudian kami bergegas pergi ke sekolah. Tepat ketika lonceng sudah dibunyikan, kami sampai di depan kelas masing-masing. Jam pertama adalah jam untuk tes matematika mingguan kami. Matematika adalah pelajaran yang membuat otakku serasa melarikan diri. Aku duduk di kursi pertempuranku di paling belakang. Di sampingku Siti duduk dengan santainya.
Tidak berapa lama menunggu, ibu Ita datang dengan lembaran-lembaran nerakanya. Setelah lembaran neraka itu dibagikan, suasana menjadi sunyi senyap tak bernyawa. Semua siswa konsentrasi dengan pekerjaannya. Seperti pada kebiasaan ibu Ita saat tes dilaksanakan, beliau akan berjalan hilir mudik membuka kotak pensil, menengok kolong meja, atau terkadang memeriksa pakaian kami. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh ibu Ita. Kolong kursi adalah tempat yang aman untuk menyembunyikan contekan. Bermodalkan permen karet, lembaran contekan itu aku lekatkan di bawah kursi. Ilmu itu aku dapatkan dari para bujangers yang sukses lulus SMA dengan nilai gemilang berkat primbon mencontek.
Saat Bu Ita mampir di meja kami. Kami mencoba santai. Bu Ita membuka kotak pensilku yang hanya berisi satu pensil dan satu penghapus. Kemudian beliau mengambil kotak pensil Siti dan membukanya pelan dihadapanku.
Tlakk…
Kotak pensil itu terbuka dan uang yang ada di dalamnya berhamburan ke lantai. Betapa terkejutnya ibu Ita saat itu, melihat jumlah uang yang tak wajar bagi kami memegangnya.
“Siti, jelaskan ke ibu ini uang apa?” tanya Bu Ita.
“Itu uang orang, Bu. Tadi tidak sengaja kami lewat di depan toko emas, karena takut uangnya diambil orang jahat. Jadi, kami ambil saja uangnya nanti baru kami kembalikan” kata Siti dengan polosnya.
Kami mengangguk saja sebagai tanda mengiyakan.
“Dengar anak-anak. Jangan sekali-kali tangan kalian mengambil atau bahkan menyentuh barang yang bukan milik kita. Apalagi mengambil uang yang jumlahnya segini banyaknya. Kalian berlima keluar sekarang!” titahnya.
Kami berlima termangu seperti orang dungu.
“Tapi, Bu! Uang itu akan kami kembalikan nanti.” sahut Egi.
“Kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena setan berada di sekeliling kita. Kalian berlima keluar dan hormat di depan bendera sampai waktu istirahat.” katanya lebih keras.
Aku mengelus dada. Siti menatapku lirih. Dimas terlihat marah karena tidak bisa melanjutkan tesnya. Dan Egi terlihat menyesali atas idenya tadi. Sementara itu Pahing terlihat bahagia karena tak jadi melaksanakan tes. Kami pun berdiri di depan bendera, menghadap sang sejarah Indonesia. Terlihat adik-adik kelas mengejek kami. Mereka terlihat bahagia dengan polosnya melihat kesengsaraan kami. Aku malu berdiri di hadapan bendera karena kecerobohan yang disengaja.
Sepulang sekolah kami digiring Bu Ita untuk mengembalikan uang itu. Sampai di depan toko. Wajahku serasa ditampar-tampar oleh pelanggan yang berada di toko itu. Egi dengan dewasanya berusaha menjelaskan perkara kejadian kepada si pemilik toko.
“Oh, uang itu. Tadi malam uang itu tidak sengaja jatuh dari dalam tas. Setelah kuperiksa di rumah ternyata tasku bolong. Tapi aku tak menghiraukan uang itu. Uangnya sudah aku halalkan. Jadi, uangnya bagi-bagi buat kalian yah!” kata si pemilik seorang ibu haji.
Senyum kesombongan mengembang di pipi kami. Kami perlihatkan ke ibu guru deretan-deretan gigi sebagai pertanda bahwa kemenangan di pihak kami.
Hukuman Kedua
Suatu hari hujan lebat menguasai kota Sampit. Saat istirahat tiba, kami berencana untuk pergi ke perpustakaan sekolah yang berada di depan bangunan sekolah kami. Itu artinya kami akan melewati hujan tanpa perantara. Basah. Itulah hasil yang akan kami petik dari aksi nekat ini. Dengan semangat mengebu-gebu, aku, Pahing, Dimas dan Egi, berlari membelah halaman sekolah yang tergenang air. Hari itu adalah hari bagi kami untuk mengembalikan buku yang telah kami pinjam. Setelah urusannya selesai kami berempat ingin segera meninggalkan perpustakaan itu. Saat kami berlari pulang, terlihat rombongan Dian juga berlari berlawanan arah dengan kami. Entah apa yang terjadi dipikiran kami saat itu. Mungkin Tuhan sudah menakdirkan kami untuk bertabrakan dengan rombongan itu. Tabrakan tak bisa dihindari. Dian dan teman-temannya menjatuhkan buku perpustakaan di genangan air. Pahing dan Egi jatuh tersungkur. Dimas lebih parah lagi, dia bertabrakan dengan seseorang bernama Bambang, yang bisa dibilang badannya 3 kali lebih besar dari Dimas. Kepala Dimas berbenturan dengan kepala Bambang, hingga membuat jidatnya berdarah. Aku hanya terduduk lesu menyaksikan kejadian itu. Tubuh kami semua benar-benar basah kuyup dibuatnya.
Kusaksikan puluhan siswa keluar dari kandangnya demi menyaksikan kami yang menderita. UKS penuh sesak dengan kehadiran kami. Sepulang sekolah barulah kami menyadari apa yang telah terjadi.
“Eg… Kartu perpustakaanku basah. Itu artinya aku harus buat lagi.” kata pahing pada Egi.
“Sama, Hing. Berarti kita harus bayar 10.000 lagi. Keluargaku sudah tak punya uang untuk hal ini.” jawab Egi.
“Pokoknya besok kita harus minta ganti rugi dari Dian. Karena dia yang menabrak kita duluan.” kata Dimas setengah emosi.
Memang begitulah keadaannya. Setiap siswa yang ingin terhubung dengan perpustakaan diwajibkan memilik kartu perpustakaan yang berupa lembaran saja seharga Rp. 10.000 untuk donasi. Mungkin Rp. 10.000 adalah nilai yang sedikit bagi sebagian orang. Tapi bagi kami, uang Rp. 10.000 itu bisa digunakan untuk membayar taksi klotok. Keesokan harinya kami menemui Dian untuk minta ganti rugi. Namun hal itu dianggapnya sebagai angin lalu. Dia malah balik menyerang kami dengan tuduhan yang tidak-tidak. Darah ini bergetar tak karuan dibuatnya. Itulah orang kaya. Kesombongan senantiasa mengelilinginya.
Niat jahat menghampiriku lagi. Inilah aku yang teraniaya oleh kemiskinan. Melihat buku perpustakaan yang terdampar di meja Dian, memberikanku peluang emas untuk membuatnya malu. Dengan diam-diam buku itu kuambil dan kusembunyikan di belakang lemari kelas kami. Dua hari kemudian, tiba waktunya untuk Dian untuk mengembalikan buku itu. Kulihat wajahnya gelisah kesana-kemari mengelilingi kelas berharap menemukan bukunya. Hatiku tersenyum lebar saat itu. Saat jam istirahat, kusaksikan Dian menghormati bendera sendirian. Di ujung perpustakaan kusaksikan Bu Ita berdiri dengan tegaknya. Tawa kami tak henti-hentinya menghiasi kantin. Hal itu ternyata membuat Dian sadar siapa pelakunya.
Keesokan harinya lagi adalah hari yang paling tidak aku sukai. Hari dimana aku harus berhadapan dengan Bu Ita lagi. Kami telah memiliki PR sebelumya. Saat bel masuk berbunyi, itu artinya kami sudah harus duduk dengan tenang dengan semua perlengkapan tertata rapi di atas meja karena Bu Ita suka dengan kerapian yang memiliki nilai plus. Saat kami berlima bersamaan mengeluarkan buku tugas, kami dibuat linglung dengan hilangnya buku kami itu. Aku bahkan dilanda takut yang mendera. Kuperhatikan wajah Dian yang berseri-seri.
“Diannnnnnnnn…” teriakku emosi.
“Apa?” katanya santai.
“Aku tahu kalau kamu yang sembunyikan buku kami!”
“Memang.” Katanya lebih santai.
“Kurang puas melihat kami menderita.” kata Egi.
“Ini adilkan? Kalian sembunyikan buku perpustakaanku. Sekarang aku yang sembunyikan buku tugas kalian.”
“Dian, bukumu akan kukembalikan tapi kembalikan dulu buku kami sebelum Bu Ita datang.” mohonku.
“Maaf sudah terlambat.” kata Dian lebih santai lagi.
Beberapa menit kemudian Bu Ita masuk ke dalam ruang. Hujan dan kemarau rasanya datang silih berganti di dalam hati kami. Kemudian Bu Ita meminta PR kami untuk dikumpulkan. Semua ini memang kesalahanku, akulah yang mula-mula membuat tiang permasalahan. Kucoba berdiri memberanikan diri bercerita kejadian yang sebenarnya kepada Bu Ita. Belum selesai aku berbicara, kusaksikan wajah Bu Ita merah membahana. Kami berlima dan Dian beserta teman-temannya, dijewer dan dipermalukan di depan bendera lagi. Sungguh aku malu berhadapan dengan bendera yang suci.
Hukuman Ketiga
Aku berjanji dalam hati untuk tidak pernah mempermalukan diri lagi di hadapan para siswa yang lain dan tentunya terhadap sang saka merah putih. Bagaimana aku tidak bisa malu? Bendera merah putih adalah bendera yang selayaknya diberi hormat karena kebanggaan, rasa bersyukur, kebahagian, dan ketentraman. Bukan diberi hormat karena suatu hukuman atas kesalahan. Aku merasa cukup dua kali saja aku dipermalukan di depan orang banyak dan di depan merah putih.
Menjelang kenaikan kelas 6, sesuatu datang menghampiriku. Di saat mengikuti ulangan, hari itu aku memakai rok putih dan batik. Belum sempat pantatku menyentuh kursi, tiba-tiba saja Siti bertertiak.
“May, rokmu berdarah.” katanya mengejutkanku.
Sontak saja aku menengok ke rokku yang memiliki bercak-bercak darah. Aku kalang kabut sendirian. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Apakah aku tadi duduk di kursi yang banyak pakunya? Atau aku salah satu korban salah tembak? Konsentrasiku tiba-tiba saja membaur. Aku gelisah mengikuti ulangan yang saat itu mata pelajaran agama islam. Kujawab pertanyaan dengan seadaanya, yang jelas aku cepat ingin keluar. Tapi aku berpikir lagi, ini adalah tes kenaikan kelas. Kalau aku sembarangan menjawab, bisa saja aku tinggal kelas.
Hatiku benar-benar galau. Suatu terobosan aneh datang menghampiriku. Entah setan apa yang menyuruhku menangis sekeras-kerasnya agar pengawas bisa menghampiriku. Aku menangis sekeras-kerasnya hingga membuat satu ruangan terkejut dan konsentrasi mereka buyar. Belum puas, kucoba untuk menangis lebih keras lagi hingga satu sekolah mengetahuinya. Sedikit kebahagian muncul ketika guru-guru kalang kabut menghampiriku. Aku tak kuasa lagi hingga kusodorkan pantatku ke hadapan mereka.
“Oh… Datang bulan. Anak zaman sekarang cepat sekali datangnya.” kata Bu Nurul.
“Yah beginilah, Bu. Beda sekali sama kita dulu yah.” kata si pengawas.
“Datang bulan itu apa Bu?” Tanyaku penasaran.
“Kamu tidak tahu datang bulan itu apa?” tanya Bu Ita.
“Kalau datang bulan itu artinya tidak perawan yah Bu? karena hampir setiap hari aku jalan sama Egi, Pahing, Dimas dan Gian” kataku polos.
“Akhh… bukan-bukan. Bukan itu. Kamu lanjutkan dulu pekerjaanmu. Nanti ibu jelaskan di kantor.” kata Bu Nurul sedikit shock.
“May, berkonsentrasilah sekarang. Nanti ada hukuman yang menanti karena kamu sudah mengganggu konsentrasi orang banyak.” ancam Bu Ita.
Oh tidak. Hukuman lagi hukuman lagi. Kejadian memalukan itu tersebar seantero sekolah. Rasanya, kalau ada sungai di sekitar situ aku ingin menceburkan diri di dalamnya dan keluar hingga malam tiba. Sejak hari itu, aku sudah merasa mulai bosan sekolah. Sepanjang jalan mereka selalu mengejekku. Bu Nurul mengajarkanku pertolongan pertama pada saat datang bulan. Aku bahagia, seandainya saja Uma bisa seperti itu. Sedikit pun Uma belum pernah menyentuh masalah datang bulan padaku. Alhasil aku dibuat shock saat darah mengotori rok putihku.
Setelah semua tes terlaksana. Tiba saatnya aku menerima hukuman terakhir di kelas 5 ini. Aku berkali-kali minta maaf kepada Bu Ita. Tapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya.
“Bu, jangan dihukum di halaman lagi yah, Bu!” pintaku penuh rintih.
“Terusss?” katanya santai.
“Apa saja, Bu! asal jangan hormat di halaman.”
“Baiklah. Silahkan kamu bersihkan WC guru yang sekarang berbau pete karena ada guru yang mungkin kemarin menghabiskan satu karung beras pete.” katanya memalingkan wajah.
Dengan sangat terpaksa kulalui hukuman itu. Menurutku itu lebih baik ketimbang dilihat puluhan siswa dan dipermalukan di depan merah putih. Biarlah bau pete yang semerbak itu menguasai hidungku. Dengan basmallah, kumulai bekerja. Namun suara langkah kaki dari belakang mengejutkanku. Ternyata itu teman-teman sejatiku. Aku bangga memiliki mereka. Dengan ikhlas mereka menemaniku bekerja menghilangkan bau pete yang merajalela.
Rumah Main
Liburan kenaikan kelas 6 kemarin, Dimas pulang ke kampung halamannya. Katanya dia melihat sebuah gua kecil di suatu taman kota. Gua itu memang sengaja dibuat untuk mainan anak-anak. Sejak itu dia punya ide untuk membuat suatu rumah main di samping pabrik. Saat istirahat di sekolah, kami berkumpul di halaman. Dimas menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan dan bahan apa saja yang diperlukan. Kami bertujuh seakan kumpulan arsitek yang sedang punya proyek besar. Perselisihan menentukan desain pun terjadi di antara kami. Batas waktu perundingan telah habis ketika bel tanda masuk kelas berbunyi. Desain sudah ditentukan. Berbentuk kotak, sederhana saja kotak. Banyak waktu yang terbuang hanya mendebatkan desain dan akhirnya pilihan jatuh kepada bentuk kotak. Harus diakui kami bukanlah arsitek handal yang bisa membuat desain bagus dan struktur bangunan yang terjamin.
Sepulang sekolah, kami bertemu di samping pabrik. Kami harus bergerak cepat karena waktu hanya sedikit sebelum matahari tenggelam. Egi, Dimas, Pahing, dan Gian pergi mencari papan-papan bekas. Aku dan Christy tidak tau apa yang harus dilakukan, sementara itu Siti belum datang. Saat papan sudah terkumpul, kami mulai bekerja membuat rumah main impian kami semua.
Egi Yosephan terlihat gagah saat peluhnya menetes ketika bermain dengan palu. Abdul Gian terlihat kuat membawa papan yang besar-besar. M. Dimas Riswan terlihat manis dengan bekerja kerasnya otaknya. Sementara Aditya Pratama Pahing, tidak ada yang perlu dikagumi. Badannya terlalu kurus, mengangkat kursi guru sepanjang tiga meter sudah separuh nyawa hilang. Dan dalam masalah pelajaran tidak ada satu mata pelajaran apapun yang dia sukai. Aku dan Christy rela menjadi pesuruh mereka mengambilkan barang yang diperlukan. Saat matahari ingin mulai bermain petak umpet. Siti datang membawakan makanan. Selain pintar menggambar, dia juga pintar dalam memasak. Tanpa pikir panjang lagi, kami serbu makanan itu.
Keesokan harinya, di taksi kelotok kami bercerita tentang rasa tidak sabarnya hati kami untuk bermain ditempat itu. Saat di sekolah, hujan melanda kawasan ini. Angin, petir, dan kilat seakan sedang beradu dalam suatu pertandingan. Perasaan takut, melanda semua hati orang-orang di kota ini. Untunglah saat pulang sekolah hujan telah reda. Sesampainya di mess, kami bergegas pergi ke samping pabrik. Saat kaki melangkah lebih dekat dengan rumah main, kami sungguh shock. Rumah yang kami buat dengan susah payah akhirnya rubuh diterpa angin siang tadi. Pondasi yang berantakan adalah penyebabnya. Kami memang tidak tahu bagaimana proses pembuatan yang baik.
Kami termangu di depan reruntuhan itu. Kami seperti anak yang kehilangan ibunya. Binggung apa yang harus dilakukan. Christy, Siti dannn… Pahing, menangis tersedu-sedu. Sungguh dramatis dan jijik melihat kelakuan Pahing. Tiba-tiba terdengar suara memanggil dari belakang kami.
“Hei… Sabarlah adik-adik kecil. Ini baru masalah kecil. Ketika kalian dewasa nanti pasti akan lebih banyak masalah. Jadilah orang yang kuat sejak kecil. Jangan menyerah pada keadaan.” kata bang Usup.
“Bang, rumah main kami hancur.” kata Christy dengan manjanya.
“Kami sudah bersusah payah membuatnya kemarin.” kataku menambahi.
“Masalah ini gampang diselesaikan, abang yang lebih punya masalah besar.” kata bang Usup.
“Masalah apa bang?” tanya Dimas dengan wajah penasarannya.
“Masalah cinta, nanti kalau kalian dewasa juga tahu rasanya jatuh cinta dan disakiti oleh cinta.” jawab bang Usup dengan yakin.
“Cinta itu apa sih bang?” tanya Siti
“Cinta itu bisa membunuh yah, bang?” tanya Pahing memusingkan bang Usup saja.
“Satu-satu lah kalau ingin bertanya. Cinta itu artinya berbagai macam rasa bersatu padu dalam harmoni di jiwa. Senang, bahagia, canda, suka, tertawa, senyum namun bisa berubah menjadi benci dan dendam” kata bang Usup.
Kemudian dilanjutkan, “Iya, cinta itu bisa membunuh dengan cara yang lembut dan pelan-pelan.” kata bang Usup menambahi.
“Aku jadi takut jatuh cinta, Bang.” kata Dimas.
“Jangan… jangan takut jatuh cinta. Tanpa cinta, manusia malah bisa gila. Pria sejati harus berani jatuh cinta. Ingat moto pria jantan, MATI SATU TUMBUH SERIBU.” kata bang Usup lagi sambil berdiri dan mengenggam tangan kanannya.
“Seperti aku, Bang.” kata Egi.
“Iya, seperti kamu yang tampan dan pemberani.” sahut bang Usup.
Seketika, wajah Egi langsung memerah saat dipuji oleh bang Usup. Padahal sesungguhnya hati kecil bang Usup melakukan demo besar-besaran.
“Cukup membahas cintanya. Kata abang masalah kami adalah masalah gampang, bagaimana cara memperbaiki semua ini.” kataku seraya bangkit berdiri.
“Tampaknya kamu kurang tertarik masalah cinta yah. Tapi tidak masalah, besar nanti kamu akan rasakan yang namanya cinta. Oke, masalah ini biar abang yang urus. Sebulan kedepan kalian jangan datang kemari. Abang punya kejutan untuk kalian nanti.” kata bang Usup dengan mata yang berbinar-binar.
“Kenapa, Bang? bolehlah kami ke sini bantu-bantu abang.” kata Dimas.
“Masalah ini biar abang sendiri yang selesaikan. Kalian jangan sekali-sekali ke sini, karena ini akan menjadi kejutan besar.” kata bang usup sambil memandang langit.
Sebulan sungguh terasa berat, kami dihantui rasa penasaran yang sangat ganas. Ingin rasanya mencuri kesempatan melihat apa saja yang dilakukan bang usup. Tapi, kami harus membuang jauh-jauh niat itu. Janji sudah kami ikrarkan dengan bang usup. Selama sebulan kami menunggu, tidak ada kegiatan spesial yang kami lakukan. Sungguh hari-hari yang membosankan.
Saat tiba waktunya, kami sangat bersemangat menemui bang usup setelah sebulan tak bertemu. Pulang sekolah kami langsung menuju ke TKP. Dari jauh terlihat ada bangunan kecil yang tersembunyi dari tingginya atap pabrik. Kami sungguh terpesona melihat bangunan itu. Di halamannya ada sebuah kolam kecil, di samping kolam itu berdiri tegak tiang bendera, dan di atasnya ada sehelai kain berwarna merah putih. Di teras depan ada tangga yang menghadang sepanjang satu meter dari tanah. Memasuki ruangan itu kami seperti ada di dunia fantasi sendiri. Di tengah ruangan tersedia meja berbentuk persegi panjang, di salah satu dinding ada susunan kayu berpetak-petak, dan di bawahnya bertuliskan nama kami masing-masing. Ternyata fungsi benda itu untuk meletakkan barang-barang kami sendiri. Yang paling membuat kami kagum adalah dinding di hadapan kami, di dinding itu ada gambar ciptaan tuhan yang hebat dan luar biasa. Peta dunia. Akhirnya kami memiliki peta dunia juga. Di dinding satunya, ada peta Kalimantan tempat kami berpijak sekarang. Belum puas menikmati ruangan itu terdengar suara bang Usup memanggil kami.
“Woy… Kawan-kawan kecil, bagaimana rumahnya?” teriak Bang Usup.
“Mantap, Bang.” kata Pahing.
“Syukurlah, ayo turun sini. Abang bawa ikan.”
“Diapakan ikannya, Bang?” tanya Pahing.
“Kita bakar, abang lapar.”
“Bakar, yes..yes..yes… kita makan” kata Gian dengan semangatnya.
Kami makan bersama, melahap ikan tangkapan Bang Usup. Tanpa terasa waktu berlalu terlalu cepat. Kami pulang ke rumah saat azan magrib berkumandang. Setiba di rumah suara ibu rumah tangga yang berkumandang menggantikan adzan magrib.
“Ikam neh darimana ja, sudah magrib ini neh. Hancapi sembahyang sana. Bulik magrib kalau pina dibantas nenek lampir di hutan sana toh.” kata ibuku dengan bahasa melayu khas Kumai.
“Enggih, Uma. Ini hendak mandi nah. Di mana ada nenek lampir, Ma?” tanyaku.
“Hancapi ja mandi tuh, kenaam bekisahnya.” jawab Uma sambil berlalu.
Begitulah Umaku, cintanya terhadap kampung halaman sangatlah besar. Beliau tidak bisa toleransi terhadap bahasa lain. Kalau sedang ada perkumpulan para ibu-ibu di mess, mereka semua berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maklumlah kami disini berasal dari berbagai macam daerah. Jadi, bahasa pemersatu kami ya bahasa Indonesia. Berbeda dengan Umaku, di manapun dia berada bahasa pemersatunya ya bahasa Kumai. Untunglah kami masih tinggal di ruang lingkup Kalimantan, jadi bahasanya masih nyambung.
Menemukan Si Nenek Lampir
Sehabis salat aku mencoba bertanya lagi tentang nenek lampir itu, tapi Uma malah menyuruhku belajar. Sampai nyala lampu menghilang dari pandangan mata, aku masih menyimpan rasa penasaran tentang nenek lampir itu. Besoknya kami pergi memancing ikan untuk dimasukan ke dalam kolam di depan rumah main. Hari itu aku merasa aneh, di dalam otakku bertuliskan nenek lampir dan nenek lampir. Apakah nenek lampir itu nyata atau cuma rekayasa orang tua untuk menakuti anaknya?

Sehabis salat aku mencoba bertanya lagi tentang nenek lampir itu, tapi Uma malah menyuruhku belajar. Sampai nyala lampu menghilang dari pandangan mata, aku masih menyimpan rasa penasaran tentang nenek lampir itu. Besoknya kami pergi memancing ikan untuk dimasukan ke dalam kolam di depan rumah main. Hari itu aku merasa aneh, di dalam otakku bertuliskan nenek lampir dan nenek lampir. Apakah nenek lampir itu nyata atau cuma rekayasa orang tua untuk menakuti anaknya?
“Hei, May. Kenapa diam saja? Pancingnya bergerak tuh.” kata Siti mengejutkanku.
“Oh iya, dapat, Sit…” kataku sambil mengangkat pancing.
“Kenapa kamu hari ini banyak diam tidak seperti biasanya.”
“Aku penasaran cerita tentang nenek lampir di hutan belakang, benar tidak yahh?”
“Oh cerita tentang nenek lampir itu, itu cerita nyata.” kata Christy mengejutkan kami.
“Dari mana adek tau?” tanya Siti.
“Eh kawan-kawan kumpul semuanya disini, aku punya cerita seru.” kata Christy sambil memanggil teman-teman yang lain.
Teman-teman yang berada di sudut tongkang lainnya berlari menemui kami, mereka melepas pancingnya demi mendengarkan cerita dari Christy yang cantik jelita.
“Begini nih Kak, Bang. Biasanya kalian dengar orang tua kita bilang nenek lampir di hutan belakang, iyakan? Kalau ditanya pasti mereka tidak menjawab. Nah, aku sudah tahu cerita yang sebenarnya dari tanteku yang kerja di kantor. Kata tanteku nenek lampir di hutan belakang memang nyata. Dulu di perusahaan sebelah sebelum perusahaan kita ini dibangun ada seorang pensiunan guru yang punya anak satu. Dulunya dia adalah guru yang baik, dia mengajar di kota. Sampai suatu saat, suaminya meninggal karena kecelakaan alat berat saat bekerja. Hal itu membuat dia sempat stress ditinggal oleh suami tercintanya. Selain itu, katanya, waktu dia mengajar dulu banyak guru yang tidak suka dengan cara mengajarnya karena dianggap tidak masuk akal. Dia terlalu cinta dengan bentuk-bentuk awan, banyak orang mengira kalau dia itu menyembah awan. Setelah itu dia diasingkan ke hutan dan anaknya sendiri saat itu sedang kuliah di daerah Jawa. Begitu ceritanya.” Christy bercerita dengan serius.
“Cerita yang mengerikan, benar-benar mengerikan.” kata Gian.
“Bagaimana dengan wajahnya. Mengerikan tidak?” tanya Pahing.
“Entahlah… mungkin saja mengerikan seperti nenek lampir di film Angling Dharma.” sahut Christy.
“Film Angling Dharma?” tanyaku penasaran.
“Iya, kalau penasaran nanti malam ke kantor saja. Kita nonton film itu sama-sama.” Christy menjawab.
“Kamu nonton film itu tiap malam?” tanya Siti lagi.
“Iya.” kata Christy dengan lantang.
“Wah… berarti tiap malam kamu tidak belajar malah jalan-jalan.” kataku.
“Kalau belajar teruskan bisa gila juga. Buktinya kita masih terus terbelakang.”
“Ayo kita pulang, ini sudah jam 5, nanti kemalaman sampai rumah. Anak perempuan pulang saja duluan, kami mau mengantar ikan ke rumah main.” potong Egi.
Kami bergegas pulang meninggalkan tongkang itu, kami takut kejadian kemarin terulang kembali. Kecuali Egi, Dimas, Gian dan Pahing, mereka pergi ke rumah main mengantar ikan untuk dimuat ke kolam. Pahing yang segera ingin pulang karena dilanda takut mendengar cerita Christy, mencoba untuk memperlaju langkah kakinya. Pahing yang terlebih dahulu sampai ke rumah main melihat sesuatu yang aneh di balik pepohon. Dengan wajah yang pucat pasi dia berlari sekencang mungkin melewati ketiga temannya yang lain tanpa ada pembicaraan sedikitpun. Egi, Dimas, dan Gian juga merasa takut melihat ekspresi wajah Pahing yang seakan melihat malaikat pencabut nyawa. Tanpa pikir panjang pula mereka juga berlari mengikuti langkah kaki seribunya Pahing.
Saat di sekolah barulah Pahing berani buka mulut, katanya dia melihat ada nenek tua yang sedang menghormati bendera. Bajunya lusuh dan kotor, rambutnya putih terurai tak tentu arah, tangan kanannya memberi hormat sang merah putih, matanya tajam menatap kain yang sederhana tapi memiliki sejuta makna untuk Indonesia itu. Saat nenek itu bepaling menghadap Pahing, air mata menetes di pipinya menelusuri jalan-jalan keriput di wajahnya.
Kami termangu mendengar cerita Pahing, terkecuali Siti, dia sibuk menorehkan pensil di buku gambarnya. Mungkinkah itu nenek lampir yang diceritakan orang-orang? Membayangkan rupanya saja aku tidak berani.
“Pahing, begini kah rupanya?” kata Siti.
Suara Siti mengejutkan kami. Dia memperlihatkan sketsa wajah yang dia gambar.
“Belum Sit, belum mendekati sempurna. Itu gambar nenek-nenek yang biasa. Nenek yang satu ini beda. Walaupun dia tua tapi terlihat beda dengan nenek pada umumnya.” kata Pahing menjelaskan.
“Maksudnya mukanya mengerikan yah, Hing?” kataku penasaran.
“Tidak juga, dia tidak mengerikan. Tapi ada yang beda dari dia.”
Kami tidak mengerti dengan perkataan Pahing. Malam harinya kami mengikuti saran Christy untuk menonton film itu. Dari film itu kami menyimpulkan bahwa nenek lampir itu jahat dan berwajah menyeramkan alias jelek. Nenek lampir ini adalah musuh bebuyutan dari Angling Dharma. Selain itu si nenek lampir juga punya seorang asisten jelek dan jahat bernama Gerandong. Tapi Pahing bilang wajah nenek yang dia lihat tidak sama dengan wajah menyeramkan nan jelek si nenek lampir di TV.
Kami dibuat pusing dengan pernyataan Pahing. Akhirnya kami memutuskan untuk menyelidikinya sendiri ke rumah main. Siti masih sibuk dengan pensilnya, dia benar-benar berusaha untuk mendeskripsikan wajah si nenek di buku gambarnya. Saat tiba di rumah main kami merasa adrenalin kami benar-benar diuji. Kami seperti komplotan pencuri yang ingin merampok. Mengendap-endap dibalik tumpukan kayu di dalam pabrik, berjingkit saat berjalan, masuk ke dalam rumah tanpa pemirsi dan tanpa suara. Tapi apa yang sudah kami lakukan sungguh sia-sia. Tidak ada siapa pun di sana. Kemudian kami mencari di sekeliling rumah main. Hasilnya juga nihil.
“Abang Pahing, abang berbohong yah?” kata Christy tanpa melupakan kemanjaannya.
“Sumpah semuanya, kemarin aku benar-benar melihatnya dengan jelas. Dengan mata kepalaku sendiri.” jawab Pahing membela diri.
“Sudahlah, lapar aku habis dibohongi bang Pahing. Ayo kita cari ranting kayu aja ke hutan, bakar ikan.” kata Gian.
Hatiku mengatakan aku percaya dengan perkataan Pahing. Aku yakin Pahing benar-benar melihatnya. Matanya tidak menggambarkan suatu kebohongan apapun. Hal ini membuat Pahing menjadi tidak bersemangat mengikuti pencarian ranting. Kami semua mencari ranting masuk ke dalam hutan, saat di dalam hutan Christy melihat ada burung yang belum pernah dia lihat. Burung itu bertengger di suatu ranting dengan menyombongkan paruhnya yang berwarna kuning. Ternyata burung itu tidak sendirian, dia datang bersama pasangannya. Dimas bilang kalau itu adalah burung Tingang, nama inggrisnya Helmeted Hornbill, ordo: Coraciiformes dan famili: Bucerotidae. Tingang adalah satwa yang menjadi maskot Kalimantan Barat, habitat dan ekologinya terancam akibat konversi hutan dan ilegal logging. Persebaran burung itu Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Kalimantan. Kami beruntung bisa melihat burung ini.
Tanpa sadar kami telah memasuki hutan terlalu jauh. Lalu tiba-tiba burung itu hinggap di pohon yang lebih besar. Di bawah pohon itu ada sebuah gubuk yang tidak terurus. Pahing menjadi bersemangat saat melihat gubuk itu, dia yakin kalau gubuk itu adalah rumah nenek yang dia lihat kemarin. Pahing mengajak kami semua untuk masuk ke dalam gubuk tua itu. Tiba-tiba saja hari berubah menjadi mendung. Di balik pohon besar, diselimuti rasa penasaran yang luar biasa, kami mencoba melangkahkan kaki lebih dekat dengan gubuk itu. Setelah cukup lama melirik gubuk itu, tidak ada tanda-tandanya kalau gubuk itu berpenghuni. Sesaat kemudian hujan mulai turun, tidak ada pilihan lain untuk tempat berteduh selain gubuk tua itu. Hujan mulai turun dengan derasnya. Kami benar-benar merasa ketakutan dan kedinginan.
Tiba-tiba saja terdengar suara_krekkk…_Itu adalah suara pintu gubuk yang tua. Jantung berdegup kencang, kaki gemetaran dan seluruh tubuh serasa diselimuti oleh es. Saat pintu itu terbuka pelan-pelan, kami dihantui rasa takut menanti wajah yang hadir dari balik pintu. Ketika wajah si nenek tepat di hadapan kami, kami merasa kaki kami berlari dengan sendirinya tanpa kompromi terlebih dahulu. Kami berlari sekencang-kencangnya menantang hujan. Biarlah baju ini basah asalkan selamat, mungkin itulah gambaran pikiran kami saat itu. Ada ular yang cukup besar lewat di hadapan kami. Kami lompati ular itu tanpa sadar kalau itu adalah ular yang besar dengan ukuran kepala sebesar tangan orang dewasa. Sesampainya di rumah main, aku baru sadar kalau Siti tertinggal di gubuk itu.
“Eg, tadi Siti kamu pegangkan?” kataku.
“Iya May, tapi di sana tadi dia ingin jalan sendiri katanya.” kata Egi sambil terengah-engah.
“Itu… itu… Itulah nenek yang aku lihat kemarin.” kata Pahing terbata-bata.
“Terus bagaimana nih, jangan-jangan Siti jadi makan malamnya tuh nenek.” kata Christy masih dengan gaya centilnya.
“Aku akan balik ke hutan menjemput Siti, kasian dia. Apa kata ibunya kalau kita tinggalkan dia di hutan. Siapa yang mau ikut?” tanyaku.
Mereka saling berpandangan satu sama lain. Aku merasakan ketakutan yang besar dalam diri mereka untuk kembali lagi ke dalam hutan. Aku juga merasakan ketakutan yang sama dengan mereka rasakan.
“Aku tidak bisa ikut, May, sebentar lagi magrib.” kata Dimas.
Aku kecewa dengan mereka yang tidak setiakawan, mereka hanya bisa memikirkan keselamatan diri sendiri. Aku memutuskan untuk masuk hutan sendirian. Air mata yang menetes di pipiku terhapuskan oleh air hujan. Sesampainya di gubuk, darahku rasanya berhenti beredar. Aku seperti berada di depan pintu neraka yang siap melahapku kapan saja. Kemudian kuketuk pintu itu pelan-pelan. Sepanjang perjalanan menuju gubuk ini tidak henti-hentinya aku berdoa, dari surah Alfatihah, AlIkhlas, Alfalaq dan Annas, dilanjutkan ayat kursi. Itulah ayat suci Alquran yang kubaca berulang kali. Saat suara pintu yang reot itu berbunyi, tubuhku langsung merinding seketika. Tak sanggup rasanya menatap nenek itu secara langsung, kututup mataku dengan kedua tanganku. Kurasakan tangan yang keriput dimakan usia menyentuh tanganku dengan lembut. Suara serak nan parau terdengar jelas ditelingaku.
“Bukalah matamu anak gadis, aku tidak akan memakanmu. Masuklah ke gubuk tua nenek, di luar sangat dingin.” kata nenek sambil membuka pelan mataku.
Di dalam gubuk kulihat Siti sedang menikmati bubur manggala yang hangat. Dia baik-baik saja. Tidak seperti apa yang aku pikirkan.
“Kemana temanmu yang lain?” tanya si nenek.
“Mereka sudah pulang, nek.” kataku gugup.
“Kamu tenang saja, nenek bukanlah nenek lampir yang kalian pikirkan. Siti sudah bercerita tentang kalian.”
Tiba-tiba saja suara ketukan pintu mengejutkan kami semua yang ada di dalam. Ternyata yang mengetuk adalah teman-teman yang lain. Aku sangat bahagia akhirnya kami berkumpul kembali. Aku yakin sebelum ke sini mereka telah mengalami pertempuran batin yang luar biasa hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul. Nenek menyuguhi kami bubur manggala dan teh hangat. Sungguh hangat berkumpul bersama di dalam gubuk yang kecil, berbeda rasanya dengan keadaan di luar yang dingin.
“Nek, kata nenek saya yang di Kumai. Bubur manggala adalah bubur yang diciptakan oleh nenek moyang kami di Kumai secara turun-temurun.” kataku agak malu-malu, karena takut dibilang sombong.
“Iya, bubur manggala adalah bubur khas Kumai. Dulu nenek belajar membuat ini juga dari teman-teman nenek di Kumai.”
Mendengar perkataan si nenek aku merasa bangga dengan kota kecamatan kecilku itu. Biasanya sehabis pulang kampung Dimas membanggakan kota Yogyakartanya, Pahing membanggakan kota Solonya, Egi dan Christy membanggakan kota Palangkaraya. Siti membanggakan kota Surabaya. Sedangkan aku dan Gian tidak ada yang bisa dibanggakan, Gian sendiri asli orang Sampit.
Setelah kenyang dan hujan mulai reda, kami pamit pulang. Saat itu waktu sudah menunjukan pukul 7 malam. Aku yakin para orang tua sudah kebingungan mencari anaknya yang hilang. Saat kami tiba di rumah main, terjawab sudah dugaanku, para orang tua sudah berkumpul di rumah main layaknya para orang tua menjemput anaknya saat pulang dari TK. Lagi-lagi kami dimarahin habis-habisan oleh orang tua kami.
“Sttt… sudah ibu-ibu, jangan dimarahin anaknya. Kita dengar dulu penjelasan mereka.” kata bang Usup mencoba dewasa di antara para ibu-ibu dan bapak-bapak.
“Eg, kamu yang kulihat pemikirannya sudah mulai dewasa. Kamu sekarang cerita, apa yang kalian lakukan di hutan?” tanya Bang Usup.
Aku dan yang lain dag-dig-dug menanti jawaban dari Egi, kami takut kalau dia bercerita yang sebenarnya pastilah kami tidak akan pernah bisa bertemu nenek lagi.
“Begini, Bang. Tadi kami ke hutan mencari ranting untuk bakar ikan. Lalu di dalam hutan kami melihat burung tingang, kami ikuti burung itu. Sampai di tengah hutan tiba-tiba hujan turun, terus kami berteduh di bawah pohon yang besar menunggu hujan reda.” ujar Egi ngeles, membuat kami lega.
Untunglah Egi pintar mengarang cerita, berbohong sedikit tidak apa-apa lah.
“Burung tingang? Kenapa kalian tidak panggil abang. Kalian sungguh beruntung bisa melihat burung tingang di hutan kita ini.”
Kami semua saling lempar senyum, mengisyaratkan keadaan sudah aman. Dan orang tua kami pun bisa menerima alasan itu. Aku menjerit di dalam hati.
“Ya Allah. Ya Tuhanku. Maafkan hamba karena telah membiarkan kebohongan ini. Jangan kau biarkan hamba dikutuk oleh Uma menjadi batu saat berangkat sekolah naik kelotok taksi jelek itu. Karena itu sungguh tidak eksotis.” rintihku.
Kebohongan itu tinggal menunggu perhitungan dari malaikat. Aku berpikir keras mencari alasan untuk menghadapi malaikat di akhirat nanti.
*****
Bersambung ke Sahabat Awan Bagian 5